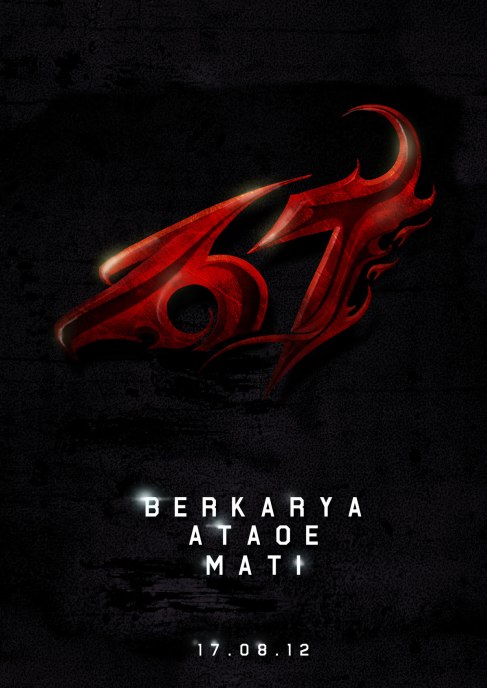Handphone kami berdering bersamaan.
Malam itu hujan. Semarak rinainya menyamarkan bebunyian apapun di ruangan yang kami tinggali. Setelah menemukan sumber suara handphone masing-masing, kami spontan memisahkan diri. Aku keluar mencari sinyal, sedang dia menuju ke ruangan lain yang cenderung tak terjamah gemuruh hujan.
Oh, aku bahagia sekali malam ini. Besok fee untuk project wallpainting di café boss-nya Ninda cair. Di dalam kepala ini, mesin otakku segera berputar dan mulai menyusun segenap rencana tentang pendayagunaan calon uang yang akan masuk ke rekeningku. Yang jelas harus beli kelengkapan perjalanan jauh, peralatan melukis, stationary, dan beberapa buku baru. Sisanya ditabung. Oh, dan satu lagi, aku pengen sedikit syukuran mentratkir dia di café boss-nya Ninda. Sekalian pamer hasil karya tentunya.
Kami bertemu lagi di ruang workshop sepuluh menit kemudian.
“Senyam-senyum aja, kayaknya baru dapet rejeki gede nih….” Ia menebak.
“Yep, dan sekalian pengen bagi-bagi rejeki” sahutku.
“Cieeh, gitu donk!” Cīnī melompat girang, “Makan dimana? Kapan?”
“Abis kita beresin maket kamu aja, sekalian relaxing. Besok sore aku traktir di café Maia!”
Cīnī tak menyahut. Ia berpikir alih-alih.
“Telpon dari siapa tadi?” tanyaku, menepis ekspresinya yang datar.
“Kayaknya kalo besok nggak bisa deh, Rul. Barusan cowok aku udah ngajakin makan duluan…”
Hatiku menclos.
Kulihat alisnya mengerut terangkat, mencoba mengisyaratkan permintaan maaf yang tersirat.
Nafasku menjadi sedikit berat.
“Oke, nggak papa kok, Cīn” tukasku singkat.
Andai ia tahu, begitu beratnya pemakluman yang kulontarkan itu. Begitu sulitnya kuberikan sedikit toleransi atas semua ini. Tapi tetap kucoba menyunggingkan senyuman untuk menghilangkan kekecewaannya. Atau sebenarnya, kekecewaanku?
“Yaay! Minggu depan ya, Rul? Okey?” Ia kembali melompat girang.
Aku hanya tersenyum sebagai jawabnya.
“Pokoknya aku tetep mau lihat hasil goresan tangan kamu yang le-gen-da-ris di café Maia” katanya sambil menunjukkan gesture khasnya yang kekanakan.
“Udah gampang, yang penting tugas maket kamu harus beres dulu!” kusentuh lembut kepalanya sambil menghilangkan sedikit kekecewaanku lewat persinggungan chemistry-nya.
Ia tersenyum manis, “Yeeey, Rula memang baiiik!”
Lalu kami kembali bekerja, menggunting kertas, memotong styrofoam, dan mengoles lem perekat yang susah hilang walau dicuci berkali-kali. Dan suasana di studioku malam itu kembali menghangat.
Aku dan Cīnī sudah cukup lama akrab. Ia adik kelasku di kampus. Pertemuan kami pun tidak sengaja, tapi terlalu menarik untuk dianggap biasa.
Sore itu, aku dapat SMS dari Pak Jazim, mantan kaprodi-ku sewaktu masih kuliah dulu di jurusan arsitek. Isi SMSnya kira-kira tentang tawaran mengisi seminar kecil-kecilan di kelas beliau. Semacam sharing dari kakak kelas yang sudah lulus. Acaranya berlangsung hari Rabu, siang hari selepas dzuhur. Adik-adik kelasku tampak begitu antusias dengan materi sharing yang kuberikan. Padahal kalau dipikir-pikir, aku ini pengkhianat jurusan. Ilmu yang kukaji selama 4,5 tahun hampir tak kupakai sama sekali. Semenjak kakiku melangkah ke dunia professional, aku lebih sibuk berkarier di bidang composing music digital dan wall décor. Yang terakhir sedikit berkaitan sih, tapi itu sudah termasuk pembenaran. Dalam acara sharing dua jam itu, banyak sekali yang antusias bertanya atau sekedar menyatakan kekaguman pada hasil karyaku. Mungkin karena hal itu pula, seusai sharing berlangsung, Pak Jazim langsung menawariku menjadi asisten beliau. Merasa tawarannya akan kutolak, ia segera pasang kuda-kuda,
“Demi almamater lho, Rul”.
Yah, meski tak bisa kuanggap cukup relevan juga, tapi kucoba memberikan jawaban sopan dan sedikit memuaskan,
“Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Sambil lihat jadwal kerjaan saya”.
Pak Jazim adalah dosen yang paling kuhormati. Selain karena cara beliau mengajar yang sangat inspiratif, karya-karyanya juga keren. Rasa hormatku kepada beliau hadir dengan begitu alaminya, hingga saat ini pun masih mengakar. Kami berpisah usai acara sharing.
Ketika kakiku menuruni tangga kampus itulah aku bertubrukan dengan Cīnī. Ia yang sedang terburu-buru, menubrukku keras sambil menggendong maket besar hingga nyaris terjengkang ke bawah. Untung aku refleks menyahut tubuhnya sehingga ia selamat dalam cengkeramanku, tapi tidak maketnya.
“Maaf mbak, saya nggak sengaja” aku buru-buru meminta maaf.
“Enggak, mas. Saya yang salah. Saya lagi buru-buru” sahutnya sambil membenahi maketnya yang sangat bernasib malang sore itu.
Aku menarik nafas panjang, “Sepertinya rusak parah. Apa yang bisa saya lakukan?”
Ia menggeleng, “Ini murni kesalahan saya kok. Mas nggak perlu tanggung jawab”
Mataku menyisir raut mukanya yang nampak amat kecewa.
“Tapi karena saya juga mbaknya jadi jatuh. Saya merasa bersalah juga, mbak. Dan, saya bisa bantu benahin maketnya kok” Sambil sedikit memaksa dan meyakinkan, aku menatap matanya lekat-lekat.
“Nggak perlu, mas. Sungguh”, ia balas memaksa.
“Cīnī, ngapain lo disitu?”
Tiba-tiba muncul suara dari anak tangga teratas. Teman-temannya datang berduyun-duyun ke bawah. Rupanya mereka anak-anak yang tadi datang di kuliah sharing-ku.
“Eh, masih ada kak Rula?” tanya salah seorang mahasiswi.
“Saya nggak sengaja nubruk mbak ini tadi. Maketnya jadi rusak”, jawabku.
“Enggak kok, saya yang kurang hati-hati” sahut gadis itu.
“Wah, itu mah lo harus bikin lagi, Cīn” celetuk salah seorang mahasiswa.
“Cīnī, lo kok nggak dateng di sharing Kak Rula sih?” seorang mahasiswi tiba-tiba bertanya, “ini lho orangnya!”
Cīnī menatapku bengong.
“Hai” sapaku.
“Wah, ini Kak Rula ya? Maaf kak, aku telat dateng soalnya tadi beresin bikin maket ini buat sekalian dikumpulin! Maaf kak, maaf!” ia menyunggingkan ekspresi memohon dengan gayanya yang lugu.
“Udah telat lo ngumpulinnya. Bakal minus 20 nilainya. Pak Jazim kejam loh!” tukas salah seorang gadis berjilbab di belakang Cīnī.
Aku mencoba mengendalikan situasi.
“Gini aja. Saya terima permintaan maaf kamu asalkan kamu ijinkan saya buat benerin maket ini. Nanti saya bilang ke Pak Jazim kalau kamu telat ngumpulin gara-gara nggak sengaja maketnya jatuh ketubruk saya. Oke?”
Ia hanya melongo menjawab permintaanku. Kulihat yang lain juga menunjukkan ekspresi serupa.
Dan sore itu, untuk pertama kali ia main ke studioku yang jaraknya tak jauh dari kampus. Dan kurang dari semalam, kami berdua menjadi akrab ketika bekerja menyelesaikan maket yang akan dikumpulkannya esok. Lima jam bekerja telah mengantarkan kami ke dalam obrolan-obrolan ringan tapi seru yang semakin mendekatkan kami.
Kedekatan ini semakin lekat ketika akhirnya kuterima tawaran menjadi asisten dosen Pak Jazim di kampusku.
“Nah, begitu donk. Itu baru namanya cinta almamater, hehe” Pak Jazim menepuk pundakku senang.
Sebetulnya bukan itu alasan saya pak, aku membatin. Aku punya alasan lain yang lebih kuat untuk berada disini. Satu nama unik kini tertambat di hatiku: Cīnī.
Setiap hari rabu, semangatku menguar setiapkali bertemu dia di dalam kelas yang kubina. Aliran endo-morphin dalam seludang otakku menjalar ke seluruh tubuh, mengemulsi elemen api yang membakar segenap energiku untuk menggelora tanpa batas. Dan semua itu hanya berakar pada satu inspirasi, Cīnī. Dia telah mengubah hidupku. Dua tahun hampa dalam badai karir yang serba hijau semu dan tak tentu arah, kini perlahan nampak nyata dan terarah. Cīnī telah mejagaku dari kelelapan yang berkepanjangan di masa silam. Dia inspirasiku.
Tapi, ketika rotasi energiku mulai perlahan stabil, badai asing itu hadir. Kejadiannya berlangsung saat kami makan bersama di kantin belakang kampus.
“Hufff….”, suaranya yang manis melenguh ketika ia ambruk perlahan di atas meja.
“Kenapa? Bete lagi?” tanyaku bijak.
“Nggak kak, cuma capek aja tadi seharian gotong-gotong properti di sekre…”, jawabnya lunglai.
Aku berdehem.
“Cīnī, gimana kalau kita buat perjanjian?”
“Eh? Perjanjian apaan?”
“Gimana kalau mulai sekarang, kamu panggil aku Rula aja. Nggak usah pakai ‘kak’ lagi deh”
“Waduh, nggak bisa kak!”
“Toh kita Cuma beda dua tahun. Iya kan?”
“Tigaaa! Korupsi nih!”
“Ya itulah maksudku…”
Ia berpikir, masih pada posisi bersandarnya.
“Biar akrab aja, Cīn…” aku menambahkan lagi.
Aku suka panggilan itu. Nama yang unik itu memberikan peluang bagiku untuk menggandakan makna panggilan sayang yang kuucapkan kepadanya. Lalu ia menyahut,
“Emangnya kita belum akrab ya, kak?”
“…Rula…”, aku mengoreksi.
“Oke, emangnya kita belum akrab ya Rul?”
“Nah! Sekarang kita resmi akrab!” aku berseru girang.
Cīnī menunjukkan ekspresi herannya dengan lucu. Dengan refleks, tanganku mencubit manja pipinya. Ia pun tersenyum.
“Okey Rulaaa! Tanggung sendiri kalau ntar nyesel loh ya?”
“Nggak akan nyesel, Cīnī…” aku balas tersenyum.
Dan makanan pesanan kami datang.
“Oh iya, tadi siapa yang bantu-bantu kamu gotong properti? Lena atau Yeni?”
Ia menggeleng sambil mengunyah suapan pertamanya.
“Bukan. Bukan dua-duanya”
“Siapa?” tanyaku acuh sambil menyeruput kuah panas soto ayamku.
“Cowokku”
“uhuk!”
Aku tersedak. Sakit sekali rasanya sewaktu kuah penuh mono-sodium glutamat itu masuk ke pipa penciumanku.
“Eh, kak, kenapa?” Cīnī panik menepuk wajahku.
“Rula! Don’t break the rule!” aku mengoreksinya sambil terus tersedak.
“Duh, ini minum dulu!” ia menyodorkan segelas air yang langsung kusahut tanpa basa-basi.
Aku meliriknya dengan tenang, dan Cīnī balas mengamati wajahku dengan tatapan gelisah.
“Kamu punya cowok…?” suaraku yang sengau kupaksakan keluar.
“Iya. Anak teknik kimia. Lho, emang kakak belom tahu?” tanyanya polos.
“Rula….”, aku mengoreksi lagi, “kamu dah janji panggil saya Rula aja….”
Ia melengus.
Dalam diam dan datar, aku lanjut menghabiskan soto ayamku buru-buru. Dan entah karena rasa sakit yang menjalar di lubang hidungku, atau anomali rasa sakit yang menyayat di hatiku, aku mendadak ingin segera meninggalkan arena itu. Meninggalkan Cīnī sendirian di sana yang mengamatiku dengan penuh keheranan.
“Saya yang bayarin, Cīn. Maaf saya mendadak inget ada perlu.”
Aku tahu alasanku terdengar kekanak-kanakan.
“Saya?” Cīnī mengernyit.
Aku terdiam mengamatinya. Aku pun tahu maksudnya.
“Sampai ketemu minggu depan ya….” Kupaksakan senyumanku saat mata kami beradu sebelum aku pergi.
Dan minggu berikutnya, aku beralasan sakit dan tak bisa hadir mendampingi Pak Jazim di kelas. Aku sendiri dibuat kebingungan oleh perasaanku. Apa-apaan ini?! Batinku memberontak. Kenapa aku jadi kekanak-kanakan begini?!
Aku cemburu.
Aku sadar aku sedikit kehilangan.
Gadis polos yang selama ini menjadi penyemangatku ternyata sudah milik yang lain. Menyakitkan sekali karena ternyata aku baru tahu kenyataannya kemarin sore. Dan yang jauh lebih menyakitkan lagi, hatiku sudah terlanjur tertambat di hatinya.
Malam itu aku kembali dirundung kesepian. Perasaan yang sama sepinya seperti sehari sebelum bertemu dengannya. Bahkan lebih buruk lagi. Serangkaian pesan singkat darinya yang masuk ke handphone-ku kuacuhkan.
Paginya aku mulai tersadar atas sikapku yang kekanakan. Aku jadi merasa bersalah kepadanya. Memangnya apa salahnya? Bukankah itu hak dia untuk punya pacar? Bukankah memang itulah sifat aslinya yang selalu baik ke semua orang? Aku saja yang ge-er!
Aku tak henti-hentinya memaki diriku sendiri.
Senin pagi aku ke kampus, menghampirinya yang sedang berjalan bersama mahasiswa yang lain.
“Boleh kita ngobrol sebentar?” tawarku sambil tersenyum tawar.
Cīnī mengernyit bingung. Sementara itu, teman-teman yang mendampinginya membubarkan diri perlahan dengan sopan.
“Aku mau minta maaf, Cīn…”
Cīnī balas menatapku lekat. Dan kuakui pada saat itu, aku kalah oleh kedewasaannya.
Kemudian, seolah tahu apa yang kupikirkan, ia bertanya balik,
“Kamu baru tahu kalau aku punya pacar?”
Aku sedikit tercekat tertahan. Kemudian aku mengangguk.
“Aku hanya sedikit kaget aja kemaren. Maaf aku dah bersikap kekanak-kanakan. Jujur, nggak ada maksud apa-apa kok” aku memaksakan senyuman di akhir kalimat.
“Oke”
“Ya?”
“Aku bilang oke, Rula…” ia menjawab dengan ekspresi datar.
“Oh, oke” aku tersenyum lagi.
Dan ia pun membalas senyumanku. “So, temenan lagi kan?”
Aku mengangguk semangat. Tapi jujur saja, dalam sepersekian detik, ketika kata ‘teman’ menggetarkan membran sel selaput keong di lubang telingaku, aku sedikit tertusuk. Aku bahkan tak yakin apakah perasaan menusuk itu ada atau tidak. Semu. Aku sudah terlanjur tersenyum.
Siang itu menandai babak baru kisahku dengan Cīnī.
Ia yang seorang gadis lugu dan setia ternyata menyimpan kedewasaan di hatinya. Setahun sejak hari itu, aku masih berteman dengannya, hingga saat ini.
Empat bulan sudah aku mengundurkan diri dari jabatan asisten dosen Pak Jazim di kampus. Urusan pekerjaan rupanya cukup membebaniku untuk membagi jadwal dengan baik. Bulan ini hujan turun dengan derasnya. Dingin yang menjalar terkadang mengemulsi kemalasanku untuk bekerja. Tapi pesan singkat yang masuk mendadak di handphone-ku seperti petir kecil yang mengejutkan mitokondria ungu di dalam sel-ku untuk mensekresikan energinya. Pesan singkat dari Cīnī yang menyatakan butuh bantuanku dalam menyelesaikan maket untuk tugas akhirnya. Di tengah hujan di malam itulah kami kembali mengakrabkan diri setelah lama tak bertemu. Kehangatan tutur katanya menyulut proses biokimia di dalam tubuhku dan melemparkanku pada keakrabanku dengannya di masa-masa awal bertemu. Semuanya belum berubah. Sikapku, sikapnya, rasaku, dan rasanya. Aku masih bisa menerima semua hal tentangnya. Satu-satunya hal yang tak bisa kuterima adalah ‘ia masih milik yang lain’.
“Udah hampir jam 5, Cīn. Gilee…” aku berujar lemah sambil bersandar di kursi malasku.
Ia melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. “Duh, ya ampun. Maaf Rulaa, kamu udah capek banget ya?”
“Eh, bukan itu maksudku. Maksudnya, kita harus buru-buru beresin biar kamu nanti ada waktu buat tidur sebelum ngumpulin maketnya” aku meluruskan.
“Ooh, ngga papa kok, santai aja. Kamu udah capek ya?”
Aku tak menjawab. Kupandangi langit-langit studioku yang kelabu.
“Cīn, café Maia itu kerjaan terakhirku di Indo”
Cīnī memandangiku heran, “maksud kamu?”
Aku membetulkan posisi dudukku, lalu memandanginya lekat yang sedang berdiri di sana.
“Minggu depan aku ke Paris. Lanjut kuliah disana. Aku dapet beasiswa dari Pak Jazim.”
Cīnī mematung.
“Kok baru ngasih tahu sekarang, Rul?”
Aku tak menjawab.
“Boleh nggak aku minta satu permintaan?” aku balas bertanya menepis pertanyaannya.
Ia angkat bahu, lalu mengangguk.
“Agak sedikit egois sih permintaannya…”
Ia angkat bahu lagi, “apapun deh Rul….”
“Boleh nggak kalau besok kamu batalin ketemuan sama cowok kamu dan sebagai gantinya kamu aku ajak makan di café Maia?”
Hening memayungi kami. Hujan semalam di luar kini mulai reda, seperti tangis anak dewa yang terkuras oleh lelah dan oleh kesedihan yang tak berkesudahan. Butir hitam matanya melirik maket yang kami karyakan bersama. Hening memperadukan hati kami sekarang.
Ia berujar, “Oke”.
Hanya itu, batinku.
Kutahan senyumanku sebelum ia menyunggingkannya terlebih dahulu.
Dan tibalah saatnya, ia tersenyum.
“Apapun akan kukabulkan buat Kakak Rula yang baik hatinya!”
Dan kehangatan kembali berdenyar.
Selewat jam dua, aku menjemput Cīnī dari kosannya, membawanya ke café Maia yang lokasinya cukup jauh di daerah atas. Setibanya disana, ia langsung histeris mengamati ilustrasi wall décor buatanku sambil tak henti-hentinya memuji. Sang pelayan yang sudah kelewat akrab denganku semenjak project yang kukerjakan di tempat ini menawarkan kami tempat duduk terbaik tepat di bawah ilustrasi buatanku. Setelah dua cangkir cokelat hangat disuguhkan di depan kami, Cīnī bertanya,
“Apa judul ilustrasi ini, Rul?”
“Algoritma Ketidakberaturan” jawabku.
Alisnya naik ketika ia menyeruput cokelat panas di cangkir bentuk hatinya.
“Apa itu maksudnya?”
Aku terdiam sesaat, pura-pura berpikir. Aku tak mau ia menebak bahwa aku sudah menyiapkan jawaban yang memang sudah kusiapkan kalau ia menanyakan pertanyaan barusan. Aku mencoba menjelaskan dengan cara lain.
“Aku mau tanya. Handphone kamu pakai nomer cantik apa nggak?”
Ia menggeleng.
“Kenapa nggak beli nomer cantik aja, Cīn?”
Ia angkat bahu, lalu balas bertanya, “Kamu sendiri, nomernya cantik apa bukan?”
Giliran aku menggeleng.
Lalu ia balas bertanya, “Kenapa kamu nggak beli nomer cantik aja?”
“Hmm”, aku berpikir. Tapi ia buru-buru menyahut,
“Jangan bilang kalau nomer kamu dibeliin sama orang atau nggak ada nomer cantik waktu kamu beli?”
Aku menggeleng sambil tersenyum.
“Bukan itu, Cīnī…”
“Lalu? Kenapa?”
“…karena aku melihat keindahan dari sesuatu yang tidak beraturan”, jawabku.
Ia menelengkan kepala sebagai reaksinya.
Aku membetulkan posisi dudukku lalu lanjut berkata,
“Banyak orang yang berpikir dengan cara mainstream. Dan pola pikir itu mengantarkannya dalam cara melihat keindahan dalam sesuatu. Hal ini bisa dipaparkan dalam konteks hukum chaos dan order. Bagi sebagian besar mereka, keindahan itu ditempuh dengan cara-cara yang lazim menurut hukum Order, seperti membeli nomer cantik misalnya. Nomer cantik dianggap sebagai suatu bentuk keteraturan yang lazim, dan dari situlah nilai keindahan muncul. Sebaliknya, mereka belum tentu akan bisa melihatnya dalam bentuk ketidakberaturan…”
Cīnī masih sedikit kebingungan.
“..dan, hubungannya sama gambar kamu?”
Aku melanjutkan, “Coba kamu lihat, gambar ini adalah gambar dua sejoli yang berhadapan tapi tidak bisa saling mendekat.” Aku menunjuk ke gambar yang kubuat di dinding.
Tapi ia tak mengikuti gerak tubuhku. Cīnī masih bergeming menatapku.
“…secara hukum Chaos dan Order, mereka seharusnya bisa dengan mudah saling bersentuhan. Tapi itu tidak terjadi. Arus sirkuit chaos mengacaukan peredaran mereka, sehingga sekalipun pada posisi yang secara Order terbilang lazim atau sangat mungkin untuk bersentuhan, tapi keduanya tidak terjadi di ranah hukum chaos. Mereka tetap tidak bisa bersentuhan. Tapi satu hal yang pasti terjadi dalam hukum ketidakberaturan itu adalah; mereka tetap terikat dalam keindahan.”
Aku menyudahi penjelasanku sambil terus menatap gambar yang menempel di dinding di samping kami. Aku tak berani menatap matanya. Mata Cīnī yang lembut tapi dalam. Bahkan tanpa perlu menatapnya, aku dapat merasakan pancaran kedalaman energi yang menghujani ragaku. Aku mengela nafas panjang.
“Aku ngerti kok maksudnya, Rul”, katanya lirih.
Baru kemudian aku berani menatapnya.
Ia cantik sekali. Sederhana, tapi cantik.
Senyuman yang melengkung tipis di wajahnya kembali menggetarkanku.
“Mungkin itu yang bisa kugambarkan tentang kita, Cīn….”
Cīnī mengangguk kecil.
“Aku juga sependapat”, katanya pelan.
Aku menunggu.
“Kamu mencoba menggambarkan satu bentuk ketidaklaziman kejadian bahwa seharusnya dengan kedekatan seperti ini mereka bisa dengan mudah bersatu…”
“Tapi itu tidak terjadi”, sahutku.
Ia tersenyum lagi.
Tiba-tiba tangannya menunjuk ke satu bagian di dalam gambar. Seutas garis yang memisahkan mereka.
“Kalau ini apa?” tanyanya.
Ini dia, batinku. Akhirnya ia menanyakan hal itu.
Aku menjawab, “itu adalah sebuah garis tanda tanya yang harus terjawab…”
Ia berpaling menatapku.
“Apa yang harus dijawab?”
Aku menjawab, “Mengapa mereka tak bisa bersatu”
Hening kembali turun menggelayuti kami. Suasana café yang semula memang sudah cukup sunyi kini seperti senyap. Seakan-akan semua bebunyian tertelan ke dalam sukma kami.
Cīnī mengangkat bahunya, dan menerka, “…mungkin karena memang tak harus dijawab. Mungkin itulah cara hukum chaos bekerja…?”
Aku menyahut, “Seandainya keduanya bertemu disaat keduanya masih sama-sama tak memiliki dan dimiliki, apa menurutmu hukum choas itu tetap akan terjadi?”
Cīnī bergeming.
Aku meneruskan.
“Apakah seandainya dulu ketika kau belum jadi milik siapapun dan lalu larut dalam keakraban denganku, mungkinkah kita bersatu tanpa harus ada garis pemisah itu?”
Mata Cīnī kini mencoba menerobos pertahananku dengan lembut. Lembut sekali.
Mulutnya terbuka, “Menurutku tetap tidak mungkin, kak…”
Jantungku terpompa begitu keras dalam satu degupan maut ketika julukan itu kembali tersandang kepadaku.
Bibirku bergetar dan bertanya, “….Kenapa?”
Cīnī tak langsung menjawab. Ia kembali menyergapku lembut dengan tatapannya.
Bibir tipisnya terbuka.
“Karena aku hanya bisa menerimamu sebagai orang yang kukagumi, bukan sebagai kekasih…”
Dan kulihat hujan di luar jendela turun.
Bersamaan dengan itu, panas membara di hatiku pun meredup.
Dan bersama itu pula, visual khayal utasan garis pemisah di dalam gambar yang kubuat memudar.
Inilah jawaban misteri yang ingin kudengar.
Jawaban yang seharusnya kutahu semenjak awal kami bertemu.
Jawaban yang seharusnya kudengar sebelum asmara yang kupercaya tumbuh dihatiku dan terus menerus menyiksaku.
Jawaban yang sanggup menahan emosiku, yang sanggup melipatgandakan logikaku.
Tapi ini semua sudah terlanjur terjadi.
Seminggu lagi aku akan meninggalkan semuanya bersama kenangan di arena ini.
Cīnī kuantarkan pulang dalam diam. Dan ketika mata kami beradu untuk terakhir kalinya, aku berucap lirih,
“Terimakasih”.
Dan ia memberikan senyuman termanis yang takkan kulupa sampai kapanpun.
—-
Jika cinta begitu mainstream, maka semuanya akan terjadi sesuai keinginan kita. Tetapi ia bekerja berdasarkan hukum ketidakberaturan, dimana justru itulah yang menjadikannya terasa indah.